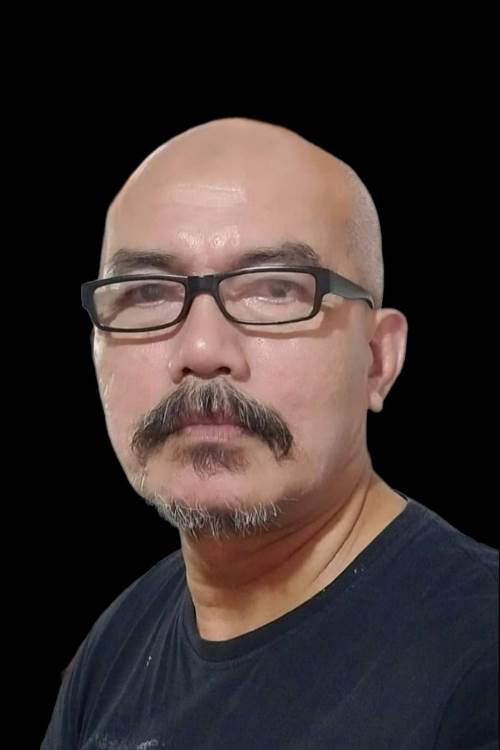Oleh : Zulkarnain Siregar
Pengantar
Judul ini tidak mengandung pretensi yang bermuara ke dalam suatu kepentingan macam apapun, tetapi sebuah keinginan yang begitu mendalam untuk berproses dalam menggagas- walaupun tidak bisa tidak mulai dari bentuk yang paling skeptis. Penggagasan ini tujuannya hanya menawarkan dialog dan menjadikannya sebagai obrolan yang cerdas dan berkelanjutan. Artinya, ketika gagasan mencapai pendulumnya, dia akan pecah dan berserak membentuk doromua-doromua baru. Namun jika pendulum itu menyentuh ruang kepentingan, maka ide menjadi “ideologi”. Ideologi akan mengatakan dirinyalah yang paling benar. Paling benar berarti mengakui adanya keterbatasan evidensi-evidensi yang lebih konkret.
Keterbatassan yang dimaksud, tentu tidak hanya berakibat menyembulnya budaya komunikasi afirmatif, tetapi peluang bertahannya komunikasi interjektif. Dominasi afirmatif dan interjektif “memandulkan” setiap pemahaman untuk dapat bertanya tentang dirinya, tentang sekitarnya dan tentang apa saja. Intensitas bertanya menjadi minus. Logikanya, proses menjadi bodoh atas setiap diri dapat diterima. Pembodohan dalam tanda kutip dilegitimasi dan menjadi sah-sah saja. Orang tidak akan pernah tercegat oleh sebuah pertanyaan yang sebenarnya bagian dari hak dan partisipasinya. Tidak merasa penting akan sebuah persoalan yang sesungguhnya bagian dari kepentingan kelayakan hidup manusiawinya. Kehidupan dan proses menghidupi “bibit” intelektualnya sangat dimungkinkan akan berhenti. Inilah yang sebenarnya yang menjadi pengantar masalah. Mulai dari sinilah pertanyaan lahir dan sikap bertanya hadir.
Ideo
Dari berbagai pidato dan banyak buku, setiap pikiran yang ada mencoba memahami tiga afirmatif tentang kebijakan setiap orang untuk sesamanya sebagai warga bangsa, yaitu: Pertama, membela sesamanya sebagai bangsa dan dalam suatu negara. Kedua, membangun sesamanya dalam kepentingan bangsa dan negara. Ketiga, menjaga sesama dalam satu bangunan-bangsa-negara. Ketiga kebijakan di atas adalah upaya perluasan moral yang setidak-tidaknya tak dapat dikatakan langsung dilakukan.Hal di atas masih berwujud dalam dunia yang melayang. Namun setelah diketahui demikian, lantas apa?
Menentukan tesa “ideologi” dari komunitas yang menegara, tidaklah kerja yang gampang, sebab sumber keyakinannya juga berasal dari kebhinnekaan. Tidak banyak sumber yang dapat membantu penguraian ideasi dari makna yang ideal sebuah “ideologi”. Hanya dapat dikatakan salah satu yang terungkap dari pesannya secara leksis adalah: ide bermakna alasan, logos bermakna sabda atau perkataan (Lihat Kamus Latin –Indonesia: halaman 397 & 501, Kanisius). Dari pemahaman di atas ada dua alternatif transformasi gramatika, yaitu: 1) alasan untuk suatu perkataan, 2) perkataan untuk suatu alasan. Arti pertama mengisyaratkan bahwa alasan diajukan untuk suatu perkataan atau diktum, sedangkan arti kedua menjelaskan bahwa perkataan disampaikan untuk menguatkan alasan. Dengan kata lain, makna pertama bermuara ke dalam bentuk dogma, selainnya, mengarah ke dialogis.
Di dalam The World Book Encyclopedia pada pengertian ideologi dalam tanda kutip: “Ideologi tidak didasarkan pada informasi faktual dalam memperkuat kepercayaan. Orang yang menerima sebuah sistem pikiran tertentu ini cenderung menolak sistem pikiran lain yang tidak sama dalam menjelaskan kenyataan yang sama. Untuk orang-orang ini hanya kesimpulan yang bertolak dari ideologi mereka yang dianggap sebagai logis dan benar. Karena itu orang yang secara kuat menganut ideologi, tentu mengalami kesukaran untuk mengerti dan berhubungan dengan penganut ideologi lain.”
Ada beberapa deskripsi dari pengertian di atas, antara lain: 1) Ideologi tidak mendasarkan diri pada data empiri yang faktual. 2) Sistem pemikiran yang menganut satu ideologi cenderung menolak sistem pemikiran dari ideologi lain. 3) Sebuah ideologi tidak pernah sama dalam menjelaskan suatu kenyataan yang sama. 4) Seorang ideolog ideologi tertentu akan sukar mengerti dan berhubungan dengan penganut ideologi lain. Bila dicermati uraian di atas maka menjadi jelas bahwa ideologi tidak pernah berhubungan dengan kenyataan-kenyataan yang berkembang dalam suatu masyarakatnya. Berikutnya, jika sistem pemikiran direduksi ke dalam ideologi, maka logikanya, pemikiran tidak akan pernah bersentuhan dengan kenyataan-kenyataan. Secara vertikal masyarakat yang menganut ideologi tertentu tidak akan pernah mengalami dinamika. Tampaknya, hipotesa seperti ini tidak mudah dipercaya, sebab dalam teori sosial dari aliran mana pun tidak ada absolutisme. Kecuali ideologi dipersepsikan ke dalam semacam “agama” masyarakat.
Oleh sebab itu, jika ideologi diromantisasi ke arah yang dogmatis maka, growth society adalah bagian dari akibat-akibatnya, walaupun ada sains sebagai “kekuatan” lain. Sebaliknya. Ideologi yang dialogis lebih representatif untuk kebutuhan masyarakat yang “dibentuk” oleh ilmu pengetahuan dan teknologi. Persoalannya adalah sejauh mana potensi yang berkembang mampu mengurangi kepentingan-kepentingan sepihak dengan menggunakan instrumen itu? Artinya ide-ide yang berkembang tetap menjadi bagian dari kepentingan makro.
Menegara
Imbuhan meng- pada kata menegara artinya menjadi. Menjadi negara. Syarat-syarat terbentuknya negara ada tiga, yaitu 1. Ada wilayah, 2. Ada penduduk, 3. Ada pemerintahan (pengelola)
Hans Kohn pernah menuliskan konsep negara, antara lain: “Negara terpusat krasi Tudor di Inggeris dan Louis XIII di Prancis belumlah sebuah negara bangsa (national state). Karna pada masa itu, negara adalah raja. Hanya ketika Inggeris di abad ke-17 dan Prancis semasa Revolusi 1789 barulah negara berhenti menjadi “negara raja”. Lembaga itu telah menjadi negara rakyat, negara nasional.”
Dari penjelasan di atas kontinuitas historis yang “membedah” ruang dan waktu. Satu waktu “negara adalah raja” dalam ruang yang berbeda. Sedangkan di waktu itu “negara adalah rakyat” dalam ruang yang sama. Penjelasan pertama cenderung berkorespondensi dengan asumsi Althusser yang memandang negara sebagai perangkat penindasan. Negara di bagun atas dasar kekuasaan dan ber”wajah” dominasi politik atas masyarakat. Selanjutnya dikatakan bahwa negara mempunyai kedudukan selalu ada di atas masyarakat.
Ada dua teori populer tentang negara, yaitu: teori kaum kapitalis dan teori kaum marxis, tetapi sayangnya, keduanya beranggapan bahwa negara tidak mandiri. Negara hanyalah ibarat kantor yang hanya menyelengarakan administrasi saja. Kekuatan sosial politiklah yang menjadi “majikan”. Dalam pandangan Hegel, negara secara apriori melayani kepentingan umum. Alasannya negara merupakan peningkatan dari pertentangan-pertentangan individual yang subyektif. Tidak rasional. Itu sebabnya dari dialektikanya, dirinya mengatakan bahwa negara merupakan penjelmaan dari kebebasan yang rasional dan mengenal dirinya dalam bentuk yang konkret dan obyektif.
Sekurang-kurangnya apa yang dikatakan Althusser dan Hegel merupakan penjelasan dari “negara adalah raja” dan “negara adalah rakyat”. Namun ketika negara dikooptasi oleh kekuasaan, makna dari premis-premis di atas menjadi kabur. Karena psikologi dari kekuasaan itu sendiri bergeser ke tingkat libido- meminjam istilah Freud.
Kuasa
Salah satu dari sekian unsur kekuatan adalah kekuasaan. Kekuasaan terbentuk karena adanya unsur penting seperti legitimasi. Legitimasi dapat diperoleh dari berbagai sumber, misalnya: massa, ideologi, dukungan, kelas sosial yang berkepentingan, teori-teori, nilai-nilai, moral, agama dan paham-paham kemanusiaan yang sekuler.
Kalau ada seorang Thomas Aquinas (1225-1274) yang menggantungkan legitimasi kekuasaan negara pada kesesuaiannya dengan tuntutan normatif fundamental: Orang lain, seperti Thomas Hobbes (1588-1679) mengapa mengambil posisi “berseberangan jalan” dengan asumsi kekuasaan akan pasti adil atau tidak adil melalui hukumannya. Artinya, Thomas yang pertama, menuntut kekuasaan tidak harus membenarkan dirinya sendiri. Kekuasaan hanyalah suatu kenyataan fisik dan sosial, tetapi tidak memuat suatu wewenang. Baginya tidak ada manusia yang secara asasi mempunyai wewenang atas manusia lain. Yang berwenang adalah sang Pencipta. Sedangkan Thomas kedua, meletakan hukum sebagai kekuasaan yang mutlak-sebagai intinya. Negara dibuat tanpa tandingan, sedangkan dapat memastikan, memaksa ketaatan para anggota masyarakatnya terhadap hukum. Negara menetapkan suatu tatanan hukum, siapa yang tidak menaati akan dihukum mati.
Ketika menjadi perdebatan versi terhadap kekuasaan dari kedua Thomas tadi, muncul paradigma lain dengan pandangan yang lebih relatif. Niccolo Machiavelli (1469-1527) adalah orang yang berpendapat tidak ada manfaatnya kalau kita mempersoalkan legitimasi kekuasaan. Yang penting adalah bagaimana untuk merebut dan mempertahankannya. Dari II Principe dia mengemukakan “Tindakan yang jahat pun akan dimaafkan masyarakat, asal saja raja (baca: penguasa) mencapai sukses. Bahwa kekejaman, asal dipakai secara tepat merupakan saran stabilitas. Lebih baik penguasa ditakuti dari pada kalau ia dicintai. Saya semakin ragu kalau masih ada J.J. Rouseau dengan konsepsi kekuasaan trias politikanya. Sesungguhnya keraguan ini: “bagaimana pun juga negara sebagai organisasi kekuasaan memusat yang secara impersonal mengontrol kelompok-kelompok masyarakat di bawahnya. Akhirnya ideo, logos dan kuasa itu sebenarnya konsep-konsep yang abstrak dan jarang menyentuh persoalan-persoalan yang real.
Namun lepas dari sifatnya itu, diakui atau tidak, pola legitimasi yang bermuara ke dalam tindakan atas nama “pembangunan” tetap memiliki instrumen itu sebagai anutannya. Liberalisme, misalnya, membenarkan pembangunanya dengan nilai-nilai kebebasan dan pertumbuhan sosialisme dengan kesamaan. Fasisme dengan kepentingan akan kejayaan bangsa. Banyak lagi paham-paham pembangunan kemanusiaan yang sekuler, yang di belakangnya berdiri ideologi-ideologi tertentu. Lantas apakah kita punya pertanyaan di samping afirmasi dan interjeksi yang ada? Semoga
*)Penulis adalah pendidik, dan penyuka diskusi.